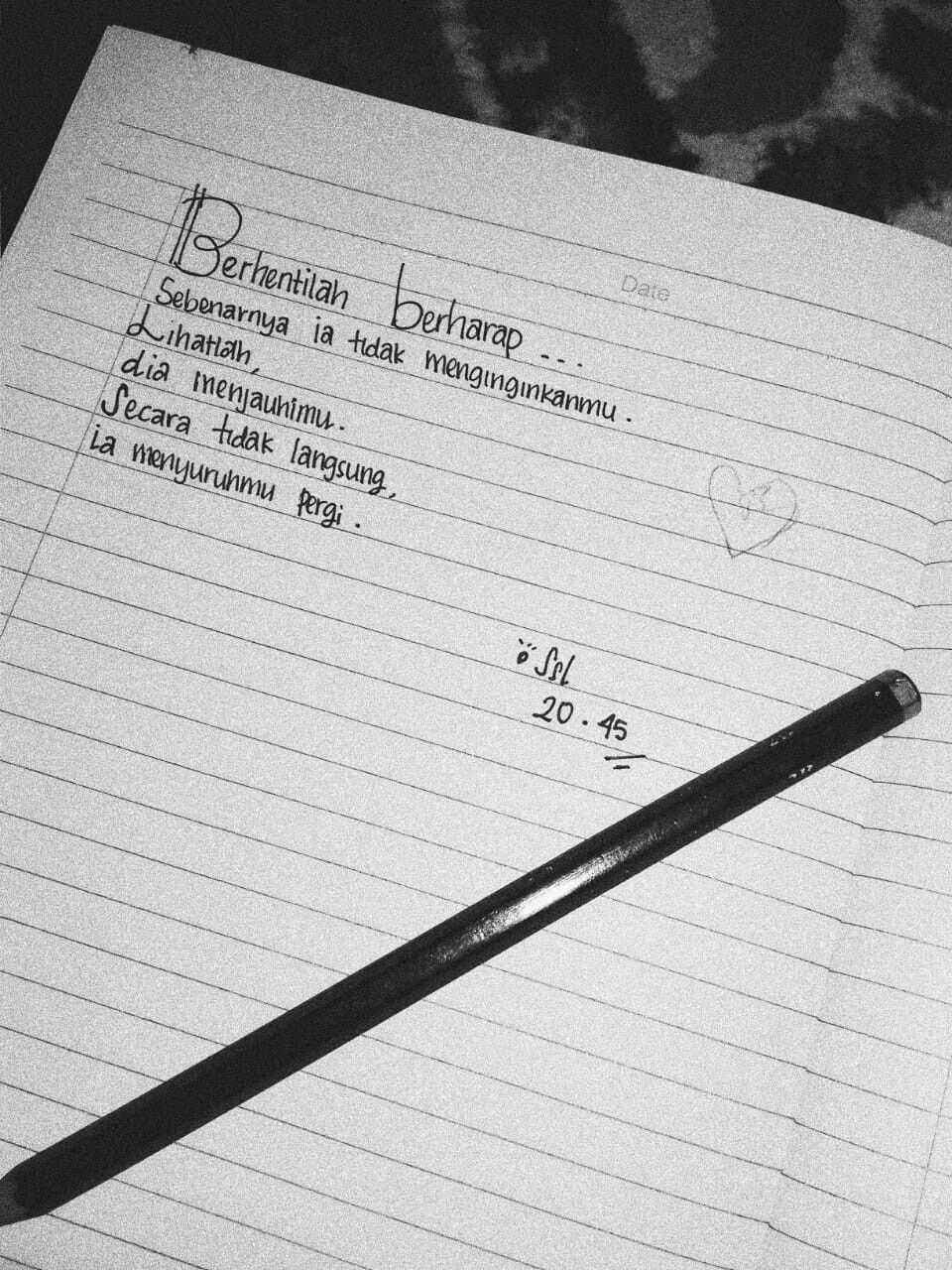Setiap malam, Damar menatap layar ponsel dalam sunyi. Hanya suara ketukan tombol dan detak jantungnya yang berpacu. Angka-angka berputar, berharap hari ini keberuntungan berpihak. Sekali saja menang besar, ia ingin membuktikan—ia masih laki-laki yang bisa dibanggakan.
Tapi malam itu, ia kembali kalah.
Saldonya nol. Lagi.
Ia mengusap wajah, keringat dingin membasahi pelipis. Di kamar sebelah, istrinya, Lita, sedang rapat daring. Suaranya lantang, tegas, percaya diri. Gajinya dua kali lipat dari Damar. Bahkan lebih.
Sejak pandemi, bisnis Lita naik. Sementara Damar kehilangan pekerjaan tetap, hanya bertahan dari proyek serabutan yang tak menentu. Mulanya, Lita masih mendukung. Tapi lama-kelamaan, ucapannya berubah.
“Mas ngerti nggak sih rasanya capek kerja sendirian sementara kamu main HP terus?”
“Coba Mas punya sedikit ambisi.”
“Kalau bukan aku yang kerja, kita udah makan pasir dari kemarin!”
Damar diam. Tapi tiap kata itu menggali lubang kecil di dalam dadanya.
Ia tak bisa balas berteriak. Ia tahu Lita tak sepenuhnya salah. Tapi luka harga diri itu pelan-pelan membuatnya ingin menang cepat, meski lewat cara tolol: judi online.
Awalnya seratus ribu. Lalu lima ratus. Lalu honor desain terakhirnya lenyap dalam satu malam.